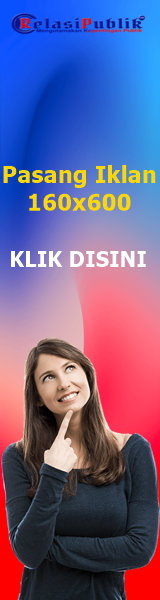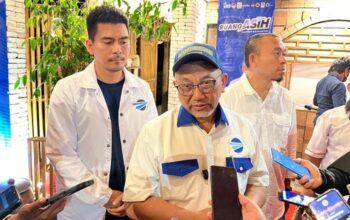Oleh : Ahman Nurdin
Cukup gemuruh. Itulah suara sebagian umat umat yang mempersoalkan status nasab habaib dengan keluarga (dzurriyyah) Rasulullah. Tergolong anyar suara gemuruh itu. Puluhan bahkan ratusan tahun lalu, suara yang mempersoalkan nasab habaib nyaris tak pernah mengemuka. Tapi, mengapa kini muncul “gugatan” masalah status nasab habaib dengan keluarga Rasulullah? Layak kita pertanyakan lebih jauh, skenario apakah yang sedang dimainkan?
Secara sosiologis, tidaklah berlebihan siapapun mempertanyakan status nasab habaib dengan keluarga Rasulullah, apalagi berjarak kisaran 1.400 tahun. Tapi, bangsa Arab punya tradisi bagaimana mengikat hubungan geneologis (nashabiyyah). Tradisi ini memungkinkan kebenaran hubungan teratas (Rasulullah) bahkan di atasnya dari garis ayah ataupun ibu dengan generasi jauh di bawahnya sampai kini.
Namun, perkembangan dan perseberan keluarga ke berbagai tanah air, juga memberi kemungkinan terjadinya “miss” atau salah catat dalam silsilah. Kekeliruan itu sangat mungkin lagi terjadi karena perkembangan politik yang telah terjadi sejak tragedi terbunuhnya Utsman ibn Affan (12 Dzulhijjah 35 Hijriyyah). Sejarah mencatat, terbunuhnya Khalifah Utsman, kekhalifahan dilanjutkan Ali ibn Abi Thalib. Sejak itu terjadi friksi politik yang cukup tajam. Ditandai dengan Perang Shiffin, antara barisan Ali ibn Abi Thalib versus barisan Amr ibn `Ash, selama tiga hari (8 – 10 Safar 37 H atau 26 – 28 Juli 657 M). Di tengah keterdesakannya, Amr ibn `Ash kibarkan bendera putih. Pertanda minta damai. Di sanalah muncul perdebatan lanjut dan tidaknya perang. Ali ibn Abi Thalib menghargai makna kibran bendera putih. Tapi, sebagian pengikutnya berbeda menyikapinya. Inilah cikap friksi politik yang cukup tajam.
Yang perlu kita telisik lebih jauh, pergolakan politik itu tidak hanya terus berlanjut dalam konteks hubungan kepemimpinan Ali dan sebagian rakyat, tapi juga memunculkan persoalan faham keagamaan. Munculnya golongan Khawarij sebagai panorama faktual terkait penentangan ekstrim terhadap kekhalifaah Ali ibn Abi Thalib. Implikasinya – minimal – terjadi deviasi sikap pro-kontra Ali, tidak hanya di wilayah politik itu sendiri, tapi juga hal-hal lain, termasuk penulisan sejarah silsilah. Barisan anti Ali ibn Abi Thalib sangat memungkinkan “menghapus atau menghapus” jalur silsilah itu, tidak hanya dengan Ali ibn Abi Thalib, tapi sampai ke Rasulullah.
Karenanya, karya-karya tentang nasab habaib dengan Rasulullah tidak tertutup kemungknan terdapat dua corak besar. Sebagian, sesuai data faktual sejarah silsilah itu. Dan Sebagian lagi, sudah terbumbui nafsu kebencian, sehingga sebisa mungkin memunculkan narasi yang menolak keberadaan nasab di antara habaib dengan Rasulullah. Inilah problem sosio-politik yang mengharuskan kita hati-hati saat menerima dan atau menolak hubungan darah habaib di Tanah Air ini dengan Rasulullah.
Kita perlu mempersoalkan, mengapa harus gemuruh mempersolkan nasab habaib dengan dzurriyyah Rasulullah? Jika memang faktual nasabnya (ada garis dzurriyah dengan Rasul), apakan keberadaannya harus diistimewakan karena pandangan “pasti masuk surga-Nya”? Rasulullah memang sangat istimewa. Namun, keberadaan keluarga – seperti halnya nasab di antara Nabi dan Rasul lainnya – tidak menjamin kepastian atau berhak secara otomatis masuk surga. Contah yang sangat faktual Kan`an, putera Nabi Nuh AS. Putera Nabi Nuh – karena membangkang pada seruan ayahnya – tercatat menjadi ahli neraka. Karena itu sebuah barometer tentang keistimewaan umat manusia yang berhak menerima surga-Nya adalah ketakwaan. Ketakwaan merupakan derajat tertinggi dan pemilik tiket sah menuju surga-Nya (QS. Ali `Imran: 198).
Dari catatan tersebut, maka kita bisa menganalisa, habaib manapun – jika memang mentaati Allah dan Rasulnya – berhak mendapatkan surga-Nya. Kita selaku habaib ataupun nonhabaib layak menghormati hamba Allah yang berkualitas akhlak dan ubudiyahnya, apalagi berderajat super mulia, katakanlah maqom waliyullah. Sebaliknya, jika ia maksiat (ingkar pada tuntunan Allah dan Rasulnya), maka status habaib atau siapapun tetap berada di an-naar selagi dirinya tidak bertaubat. Untuk itu, kita semua tak selayaknya mengagungkan dan atau mendeskreditkan kaum habaib secara personal ataupun keluarga. Semuanya, berstandar pada kualitas keaimanan dan ketakwaannya. Inilah Maha Adil Allah dalam memandang.
Sekali lagi, tidak pada tempatnya kita semua “menelanjangi” atau menjelek-jelekkan habaib, yang bernasab sampai ke Rasulullah atau tidak. Sebab, jika habib yang dideskreditkan itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah, maka tindakan penyudutan itu sama artinya menyakit diri Rasulullah. Dan Muhammad ibn Abdillah bin Abdul Mutthalib memang tidak ridha. Bahaya dari sisi keagamaan. Untuk dan atau atas nama kehati-hatian, lebih baik kita hindari sikap membenci atau mengumbar narasi jahat kepada habaib. Sisi lain, bagi diri kaum habaib pun tak perlu reaksioner menghadapi catatan kritis publik, karena – secara faktual – memang ada yang benar dan salah dalam catatan nasab sampai ke Rasulullah. Dan posisi benar-salah itu – sekali lagi – tak lepas dari dinamika perkembangan sejarah umat Islam sejak zaman Khalifah Utsman ibn Affan, sampai ke perkembangan Dinasti Muawiyah dan Abbasiah, bahkan lebih jauh selanjutnya.
Kita perlu mempertanyakan, apa untungnya mempersoalkan apalagi menelanjangi masalah silsilah habaib sampai ke dzurriyah Rasulullah? Dalam perspektif keagamaan, jelaslah berdosa bagi siapapun yang menggunjing sesama hamba Allah (Q.S al-Hujurat : 12). Bagai memakan bangkai saudaranya sendiri. Namun, mengapa kini muncul penggunjingan yang demikian bergemuruh, sampai-sampai melakukan riset secara serius? Sekali lagi, riset itu tidak akan mencapai kebenaran obyektif mutlak. Sebab, rujukan penulisan silsilah sangat mungkin akan menjumpai sumber yang sudah tercemari sikap subyektivitas sang penulis. Tergantung, rujukan mana yang mau dipakai.
Yang perlu kita mencermati, gemuruh anti habaib dalam kontek keindonesiaan saat ini. Tak bisa dipungkiri, posisi mereka di Tanah Air ini bagian integral dari keberadaan umat dan sejarah negeri ini. Ikatan moral dan sosiologis-agamis habaib dan umat cukup kuat. Bahkan, kadang berlebihan. Kohesivitas mereka – perlu kita catat – merupakan kekuatan umat di Tanah Air ini. Sementara, sinergisitas ini menjadi pengganggu pihak lain yang sedang dan terus mengejar kepentingan sempitnya, dari sisi ekonomi, bahkan politik dan akidah.
Tak bisa dipungkiri, banyak elemen lain (sebagai bangsa, atau korporat, bahkan sebagai elemen ideologis komunis) berkepentingan untuk terus melemahkan umat sebagai entitas besar di Tanah Air ini. Karena itu politik devide et empera menjadi strategi yang sangat tepat untuk agenda besar meloyokan kekuatan umat. Itulah yang harus kita sadari bagi komponen muslim manapun, termasuk kaum habaib. Keduanya tak perlu tersulut emosinya, apalagi memuncak, saat muncul “gugatan” terkait silsilah ke dzurriyyah Rasulullah. Emosionalitas itu hanya mempermuluh agenda setting menuju konflik vertikal-horisontal.
Kita harus sadar, jangan mudah diadu-domba. Persoalan benar dan tidaknya silsilah di atara habaib, kita pasrahkan fakta sejarah mereka. Tak perlu klaim. Justru, secara paedagogis, siapapun di antara habaib – jika memang dzurriyah Rasulullah – ia atau mereka harus mampu memberikan keteladanan terbaik, dari sisi ketakwaan atau amaliah ghairu maghdlah. Ada panggilan moral. Sisi lain, bagi kita yang bukan habaib juga perlu menunjukkan keteladanan imaniyyah. Karena definisi “keluarga” bisa diterjemahkan lebih jauh. Yaitu pengikut, yang siap naik bersama “kapal besar” Rasulullah. Selamatlah kita semua sebagai keluarga besar Rasulullah, karerna nasab ataupun keimanannya.
Jakarta, 02 Juli 204
Penulis: anggota Dewan Pakar DPP PKS